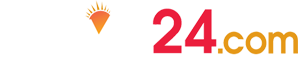50 Tahun PDIP: Antara Oligarki dan Wong Cilik

OLEH: UBEDILAH BADRUN
50 tahun lalu, tepatnya 10 Januari 1973 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berdiri. Saat itu Presiden Soeharto membuat kebijakan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai dengan tujuan menciptakan stabilitas politik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional.
Partai yang berfusi menjadi PDI adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik.
Dipinggirkan dan Terbelah
Para pengikut Bung Karno sering menyebut peristiwa fusi partai tersebut sebagai bagian dari upaya Soeharto mengikis pengaruh Bung Karno dalam politik nasional.
Tidak hanya melakukan fusi partai, rezim orde baru juga secara halus telah meminggirkan peran politik keluarga Bung Karno termasuk anak-anaknya. Hal itu terkonfirmasi ketika Megawati terpilih sebagai Ketua PDI dalam Kongres Nasional tahun 1993 di Surabaya, saat itu pemerintah orde baru tidak mengakuinya.
Kemudian pemerintah mendukung Suryadi sebagai Ketua Umum PDI hasil Kongres Nasional 1996 di Medan, saat itu Megawati Soekarnoputri tidak diundang. Perlu diingat bahwa Sepanjang orde baru PDI selalu menjadi partai yang kalah.
Terbelahnya PDI tidak bisa dihindari dan semakin runcing hingga terjadi peristiwa berdarah pada 27 Juli 1996, terjadi penyerbuan di kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro Jakarta. Peristiwa 27 Juli 1996 ini dikenal sebagai 'Kudatuli' (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli).
Terbelahnya PDI makin memuncak, ada PDIP yang dipimpin Megawati dan ada PDI yang dipimpin Suryadi. Megawati terus melawan dan terus mengkonsolidasikan jejaringnya. Megawati menjadi simbol oposisi terdepan selain Gus Dur dan Amien Rais. Posisi Megawati yang konsisten berseberangan dengan kekuasaan itu terjadi hingga tumbangnya orde baru pada tahun 1998.
Pemerintahan transisi yang dipimpin B.J Habibie membuka keran demokrasi, partai-partai politik baru boleh berdiri, termasuk PDIP akhirnya dilegalkan menjadi partai politik resmi pada awal tahun 1999, beberapa bulan jelang pemilu tahun 1999.
Pada Pemilu 1999 itu PDIP ikut menjadi peserta pemilu, atas konsistensinya berseberangan dengan orde baru, menjadi anti tesis orde baru, PDIP akhirnya menjadi peraih suara terbanyak dengan perolehan suara 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi.
Namun sayang pemenang pemilu tetapi Ketua Umumnya (Megawati) saat itu tidak menjadi Presiden. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) justru yang menjadi Presiden. Megawati menjadi Presiden setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001.
Setelah 2004 PDIP menjadi oposisi selama sepuluh tahun dan kemudian kembali berkuasa sejak pemilu 2014 dan 2019 yang memperoleh suara 19,33 %, berkuasa hingga saat ini.
Lima Episode PDIP
Episode 1973-1995 adalah episode PDI hanya sebagai pemanis demokrasi prosedural. Saat itu PDI menjadi peserta pemilu dan mendapat kursi di DPR dengan jumlah yang paling sedikit dibanding partai lain. Selama itu, hampir tidak ada peran dalam menentukan arah bernegara.
Episode kedua adalah pada tahun 1996-1998. Episode ini bisa disebut sebagai episode keterbelahan sekaligus perlawanan. PDI terbelah. PDIP yang dipimpin Megawati secara manifest menunjukan perlawananya pada perilaku otoriterian. PDIP saat itu berhasil membentuk pandangan publik sebagai partai 'wong cilik', partainya rakyat kecil, penjaga republik sekaligus penyelamat demokrasi.
Pada episode 1999-2004 atau episode ketiga adalah episode pelembagaan dan kembali berkuasa pasca orde baru. PDIP secara kelembagaan resmi sebagai partai politik yang legal dan menjadi peserta pemilu, menjadi pemenang, berkuasa di parlemen dan eksekutif (Megawati jadi Presiden) meski sempat tertunda berkuasa karena sebelumnya Gus Dur yang justru jadi Presiden.
Pada 2004-2014 adalah episode keempat PDIP. Episode ini bisa disebut episode oposisi. Karena sepanjang 10 tahun PDIP di luar pemerintahan. Menjadi oposisi dari pemerintahan SBY.
Episode kelima terjadi pada 2014-2024. Episode ini bisa disebut episode paling problematik bagi PDIP. Pemenang pemilu, berkuasa, tetapi secara umum gagap menterjemahkan ideologi dan visi politiknya dalam menjalankan kebijakan dan program-programnya di pemerintahan.
Kegagapan ini terjadi karena antara ideologi dan visi partai dengan mereka yang berada di eksekutif dan legislatif banyak yang tidak nyambung, mungkin juga tidak paham atau kalah oleh kekuatan lain yang mengendalikan Presiden Jokowi.
Nasib Wong Cilik
Secara ideologis historis PDIP sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno, ayah dari Megawati. Partai ini berideologi Pancasila dengan nasionalisme sebagai spirit dan paradigma perjuanganya.
Pemikiran bung Karno tentang Marhaenisme menjadi salah satu orientasi utamanya dalam menjalankan kekuasaan. Memanusiakan wong cilik, berpihak pada wong cilik, itulah makna substantif marhaenisme. Kemudian ingin mewujudkan apa yang oleh Bung Karno disebut sebagai Tri Sakti. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.
Ketika berakhirnya orde baru harapan 'wong cilik' pada PDIP sangat besar. Oleh karenanya pada pemilu 1999 PDIP mendapat suara tertinggi hingga 33,74 persen. Harapan wong cilik yang besar tersebut kandas, Megawati berkuasa sangat singkat setelah Gus Dur.
Sejumlah kebijakan Megawati terlihat sangat problematis terutama terkait aset BUMN dan BLBI. Pada pemilu 2004 Megawati kalah oleh SBY dalam pemilihan presiden secara langsung, partainya juga kalah.
Ketika menjadi oposisi selama 10 tahun, harapan 'wong cilik' kembali tinggi terhadap PDIP. Karenanya pada pemilu 2014 PDIP kembali menjadi pemenang pemilu meski hanya mendapat suara 18,95% suara nasional dan 19,33% pada pemilu 2019.
PDIP mengusung Jokowi sebagai calon Presiden dan terpilih menjadi Presiden, berkuasa hingga saat ini. Pertanyaanya bagaimana nasib wong cilik saat ini?
Dalam tiga tahun terakhir ini faktanya nasib wong cilik sering diabaikan. Misalnya buruh, petani, nelayan secara jelas menolak UU Omnibus Law (Ciptaker) tetapi pemerintah dan DPR tetap ngotot untuk mengesahkan.
Meskipun kemudian diputuskan oleh MK bahwa UU Ciptaker tersebut inkonstitusional dan ada amar putusan agar pembuat undang-undang memperbaikinya selama dua tahun. Tetapi kini Presiden Jokowi justru membuat Perpu Ciptaker yang dinilai oleh banyak pakar hukum tata negara sebagai langkah yang mengabaikan putusan MK dan mengabaikan UUD 1945 karena tidak memenuhi syarat suasana kegentingan yang memaksa.
Secara substansi isi Perpu 2022 juga mengabaikan wong cilik (buruh dan rakyat jelata) terutama tentang penentuan upah dan buruh outsourching. Selain itu, isi Perppu juga berpihak kepada oligarki pebisnis tambang, di antaranya karena ada aturan royalti 0% dan konsessi tambang yang otomatis.
PDIP juga adalah partai yang mengusung nasionalisme dan kebhinekaan. Tetapi faktanya justru disintegrasi sosial marak terjadi saat PDIP berkuasa. Demikian juga demokrasi semakin memburuk justru saat partai yang melekat pada namanya ada kata demokrasi ini berkuasa.
Skor indeks demokrasi Indonesia saat ini masih di bawah 70, tepatnya 6,72 masuk kategori flawd democracy (The Economist Intelligence Unit, 2022). Prof Edward Aspinall (2019) dari Australia National University (ANU) dan sejumlah ilmuwan terkemuka lainya pernah menyebut bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi.
Pengabaian terhadap wong cilik juga sesungguhnya terjadi pada 2019. Ketika DPR ngotot revisi UU KPK mengabaikan aspirasi rakyat banyak, mengabaikan aspirasi wong cilik yang sudah muak dengan korupsi. Lebih menyedihkan lagi praktek korupsi terus merajalela.
Faktanya memang Indeks Korupsi Indonesia masih di bawah 50, persisnya skornya 38, di bawah rata-rata global yakni 43 (Transparency International, 2022). Lebih menyedihkan lagi yang dikorupsi adalah bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil. Suatu praktik jahat yang melukai wong cilik.
Kondisi sosial ekonomi wong cilik juga sesunguhnya memprihatinkan. Angka pengangguran mendekati 9 juta (BPS,2022). Jumlah orang miskin juga masih memprihatinkan, angkanya hampir 30 juta penduduk (IDEAS, 2022).
Di tengah kemiskinan yang masih memprihatinkan itu kekayaan pejabat justru naik hingga 70,3 % (KPK, 2021). Mirisnya, satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional (TNP2K, 2020). Selain itu ada sepuluh orang paling kaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Di mana wong cilik ditempatkan?
Menariknya Presiden Jokowi diklaim sebagai Presiden yang berasal dari wong cilik, tetapi sejumlah keputusan dan regulasinya justru berpihak pada oligarki. PDIP berdalih Jokowi itu petugas partai.
Uniknya sebagai petugas partai ia memiliki pasukan relawan yang bukan kader PDIP. Relawanlah bersama sejumlah menteri yang memunculkan wacana tiga periode dan penundaan pemilu. Wacana yang sempat ditegur Jokowi lalu dibiarkan Jokowi.
Wacana tiga periode dan penundaan pemilu ini secara tegas ditolak oleh Megawati Soekarnoputri. Jokowi memang lebih terlihat menaati oligarki dibanding kepada Megawati. Apakah ini yang oleh Megawati disebut berkhianat? Ya, oligarki versus wong cilik sedang berkecamuk di negeri ini.***
Penulis Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Sumber:rmol.id