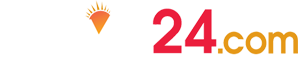Saweran dan Gegar Tradisi

Oleh: Fathorrahman Ghufron
SEJATINYA lantunan ayat suci Al-Qur’an didengar dan diresapi penuh hikmat agar setiap buliran ayat bisa menyentuh dan menembus setiap relung jiwa dengan nikmat. Bahkan, lantunan ayat Al-Qur’an yang dicerna dengan baik, setiap getaran bunyinya akan membuat yang mendengar akan menangis. Inilah penggambaran surat Al-Anfal ayat 2 tentang tanda-tanda orang-orang yang akan bertambah kuat imannya dan akan menambatkan hatinya (tawakal) hanya kepada Allah.
Hal ini pulalah yang dialami Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: “Suatu ketika Nabi SAW berkata kepadaku, “Bacakanlah AL-QUR’AN kepadaku.” Maka kukatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, apakah saya bacakan AL-QUR’AN kepada Anda sementara AL-QUR’AN itu diturunkan kepada Anda?”. Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku.” Maka aku pun mulai membacakan kepadanya surat An-Nisaa’.
Sampai akhirnya, ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya), “Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka.” (QS An-Nisaa’: 40). Maka beliau berkata, “Cukup sampai di sini saja.”
Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata.” (HR Bukhari dan Muslim). Lalu, ketika ada suatu keadaan yang mana orang sedang membaca ayat Al-Qur’an diganggu dengan perilaku tak senonoh, berupa saweran uang, tentu tindakan tersebut telah menodai prinsip utama ajaran Al-Qur’an.
Terlebih lagi lantunan Al-Qur’an dibaca saat peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diyakini sebagian besar umat Islam sebagai momen pemujian terhadap sosok panutan yang sangat sakral, memicu timbulnya kecacatan moral yang sangat akut.
Gegar tradisi Dalam kaitan itu, peristiwa naif yang terjadi di Pandeglang, Banten, (5/1/23) menjadi pembelajaran bagi siapa pun yang terbiasa menjadikan hajatan sebagai repertoar saweran. Seorang qariah bereputasi internasional yang diundang dalam forum sakral seharusnya diperlakukan sebagai tamu agung yang steril dari berbagai malapraktik hiburan tak beretika.
Bahkan, sang penyelenggara acara maulid yang sudah menyiapkan acara peringatan maulid sebagai peristiwa keagamaan yang bernilai spiritual seharusnya menggunakan sistem keprotokolan yang berbeda dengan hajatan umum. Itu disebabkan bagi masyarakat yang terbiasa memanfaatkan hajatan apa pun sebagai ajang unjuk saweran, terkadang lepas kontrol dan dengan serampangan akan memanfaatkan panggung hajatan itu sebagai media menghambur kesenangan.
Padahal, sebagaimana pepatah Arab ‘li kulli barnamijin maqamun wa nidzamun’ (setiap acara ada ketentuan dan aturan yang berlaku). Namun, sebagian masyarakat kita sering kali alpa bahwa tidak semua hajatan yang di dalamnya ada sosok perempuan yang sedang ‘manggung’ dengan corak profesi dan kemampuan bersuara yang indah harus diperlakukan sama.
Seolah-olah masyarakat kita, terutama pelaku saweran yang terjadi di Banten, melakukan generalisasi terhadap sosok biduwati yang tampil di panggung hiburan yang tetap patut diperlakukan serupa, yaitu menghambur atau menyelip uang di sela pakaian perempuan yang sedang tampil di panggung. Atas kejadian di Banten tersebut, tidak terlalu berlebihan bila banyak kalangan, baik dari unsur masyarakat awam maupun kelompok panutan, mengekspresikan kekecewaan dan kemarahannya terhadap dua pelaku saweran itu.
Beberapa tokoh, seperti di MUI, NU, Kementerian Agama, dan kaum moralis lainnya, mempunyai penilaian yang senada terhadap kasus di Banten bahwa peristiwa tersebut mencerminkan tindakan tak beretika dan tak bermoral.
Meskipun sebagian masyarakat ada yang beralibi bahwa tindakan nyawer terhadap qariah di Banten dipengaruhi tradisi menghambur uang di Pakistan, ada modus operandi yang tak serupa antara Indonesia dan Pakistan. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia masih mempertahankan jangkar keadaban dan etika ketimuran sebagai lanskap bertradisi yang mempertermukan antara kearifan lokal dan ajaran Islam.
Karena itu, ketika ada praktik tradisi yang dilakukan sekelompok orang, tetapi bertolak belakang dengan jangkar keadaban dan etika ketimuran yang disepakati bersama (‘urf), tradisi tersebut tidak bisa diterima sebagai panduan moral. Itu disebabkan secara antropologis, bangunan tradisi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia tidak hanya dipertemukan oleh irisan akulturasi yang menempatkan kebudayaan dan agama secara independen atau bahkan terpisah antarkeduanya.
Akan tetapi, keduanya ditempatkan dalam sistem inkulturasi yang mana salah satu aspek yang memiliki prinsip moralitas dan panduan kebaikan yang paling kuat itulah yang paling dominan sebagai penentu titik leburnya (melting pot) kebudayaan dan agama. (Ali Sodikin, Antropologi Al Qur’an).
Dalam konteks ini, tradisi saweran yang menjadi salah satu bagian dari fenomena panggung masyarakat Indonesia bukan berarti diabsahkan sebagai penentu umum (common denominator) yang layak diperlakukan dalam hajatan apa pun. Justru harus ada sensitivitas kearifan lokal ketika ingin memperlakukan tradisi saweran sebagai salah satu bagian ekspresi kebahagiaan pelaku hajatan.
Hal itu penting dilakukan agar tidak terjadi benturan tradisi yang bisa berdampak pada perusakan sendi-sendi kearifan lokal di Indonesia yang selama ini sudah dinapasi jangkar keadaban dan etika ketimuran. Itu disebabkan tradisi saweran yang sebenarnya mempunyai tempat dan peminatnya sendiri, tetapi tidak dipergunakan sesuai kondisi dan peruntukannya akan terjadi benturan eksternal yang bisa memengaruhi fungsi sosiologis dari saweran tersebut. Dampaknya, saweran mengalami cedera kebudayaan yang akan distigmatisasi sebagai perusak moral oleh sebagian besar masyarakat.
Oleh karena itu, agar saweran tidak mengalami benturan tradisi (clash of tradition), kita harus menyadari bahwa dalam momen tertentu ada perlakuan yang berbeda bagaimana kita mengekspresikan saweran sebagai cara berderma di dunia panggung atau hajatan. Semoga peristiwa di Banten tidak berulang lagi agar benturan tradisi tidak dimanfaatkan sebagai arena komodifikasi hiburan yang bisa jadi memecah belah kohesi sosial bangsa Indonesia.***
Penulis: Wakil Katib PWNU dan Pegiat di Center for Sharia Finance and Digital Economy (Shafi ec) UNU Yogyakarta
Sumber: mediaindonesia.com