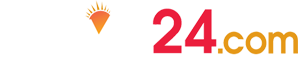OPINI
Refleksi Dua Dekade Kebebasan Berpendapat dan Pers dalam Demokrasi Indonesia

Oleh : Gilang Ramadan
KITA bisa melihat bahwa hubungan erat antara kebebasan pers dan demokrasi merupakan keterkaitan yang tidak bisa dibantah. Negara-negara dengan pencapaian pembangunan sosial yang seimbang dan sistem demokrasi yang stabil; adalah negara-negara yang menghormati HAM secara esensial, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Pada beberapa konteks, sering kali konsep-konsep indikator tersebut muncul sebagai sinonim, atau kadang-kadang mereka dapat berdiri sendiri, tetapi biasanya mereka terhubung dan saling melengkapi. Kebebasan berbicara merupakan buah pikiran yang otonom- setiap orang menerima gagasannya sendiri, membagikannya, dan menggunakannya untuk menemukan perkembangan diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, pada tingkatannya memiliki 2 hal:
1) individu-memungkinkan semua manusia untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dalam bentuk apa pun dengan cara apa pun;
(2) bersifat sosial-mengacu pada hak masyarakat untuk mengakses informasi, terutama jika itu untuk kepentingan publik.
Pada tahapannya, kedua hal tersebut telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa dekade terakhir sebagai dampak dari perkembangan akses ke platform digital. Pada saat yang sama, terjadi perluasan ketersediaan informasi publik yang merupakan elemen mendasar untuk audit sosial, akuntabilitas, transparansi dalam penggunaan sumber daya publik, dan banyak elemen penting lainnya untuk pemerintahan yang efisien guna mendorong kebaikan bersama dan pembangunan manusia yang egaliter.
Demokrasi Indonesia telah berlalu lebih dari 20 tahun; sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sejak 1999 (setelah India dan Amerika Serikat), Indonesia telah mampu melaksanakan pemilu nasional (legislatif dan presiden) dan pilkada (kepala daerah) secara teratur dengan lancar dan aman (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019).
Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, pakar politik yang memahami Indonesia dengan ‘fasih’, menyebut bahwa demokrasi Indonesia kini berada di titik terendah dalam 20 tahun (The Jakarta Post, 21/9/2019). Mereka menyatakan dalam tulisan-tulisan lain tentang apa yang mereka sebut sebagai 'paradoks demokrasi Indonesia' yang semakin nyata.
Kebebasan pers Mereka mencermati berbagai aspek kehidupan dan dinamika politik sejak periode terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan era Presiden Joko Widodo. Aspinall dan Mietzner menyebutkan, Indonesia tidak (lagi) damai sepenuhnya.
Sebaliknya, ia menentang menjadi semacam bentuk pemerintahan demokratis yang tidak liberal atau bahkan demokrasi yang cacat. Meski begitu, dalam konteks itu, pada satu sisi Indonesia tetap memenuhi syarat demokrasi elektoral. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebebasan pers (PFI) secara nasional yang menunjukkan peningkatan.
Dari hasil survei Dewan Pers Januari-Desember 2021 di 34 provinsi di Indonesia, diperoleh PFI 2022 secara nasional sebesar 77,88. Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 1,86 poin dibandingkan PFI 2021. Namun pada sisi lain, ciri-ciri yang disebut sebagai demokrasi penuh masih mengalami penurunan, seperti berkurangnya kebebasan berpendapat dan pers; serta melemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Selain itu, ruang pers juga dirampingkan dalam perubahan RKUHP, sehingga Dewan Pers mengkritisi secara tajam revisi RKUHP dan memberikan masukan terhadap isi draf tersebut sebelum dibahas kembali dan disahkan serta diundangkan sebagai pengganti hukum pidana.
Undang-undang ini menegaskan bahwa ikatan antara demokrasi dan kebebasan berbicara bersifat sangat kategoris. Oleh karena itu, tidak mengherankan melihat bagaimana negara-negara melemah kala kebebasan pers atau akses ke informasi publik semakin berkurang.
Terbaru, terjadi di El Salvador ketika pelemahan demokrasi berjalan beriringan dengan ancaman, serangan, dan reformasi legislatif yang bertujuan untuk membatasi upaya jurnalistik melalui undang-undang yang mengkriminalisasi penyebaran informasi.
Selain itu, juga terjadi serangan verbal terus-menerus, dan baru-baru ini terungkap bahwa beberapa jurnalis menjadi sasaran pelanggaran privasi (hacking) melalui program Pegasus spyware, yang telah digunakan di negara lain dengan tujuan yang sama.
Ini adalah pelanggaran yang mengerikan dan bentuk kerentanan bagi kerja jurnalistik. Kerentanan jurnalisme juga terjadi pada negara-negara yang telah lama menjadi role model of democracy seperti Amerika Serikat. Selama pemilihan presiden terakhir, AS mengalami gangguan proses demokrasi yang serius.
Penyebaran informasi publik yang diatur oleh kekuasaan telah tumbuh menjadi ruang sempit dan paradoks. Penyebaran informasi yang berbeda pendapat dengan pemerintah, menjadi syarat sebagai 'musuh rakyat'.
Dampak yang berarti dari tidak adanya kebebasan pers dalam proses demokrasi adalah nihilnya transparansi dan pengawasan sosial. Seperti yang telah kita saksikan selama pandemi, kurangnya akses informasi kepentingan publik berdampak buruk pada berkurangnya kemampuan negara dalam menangani situasi darurat dan mengurangi kemungkinan masyarakat terkait akses atau minat untuk berpartisipasi dalam isu-isu kepentingan nasional.
Ini juga mengurangi kepercayaan warga negara terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan menjauhkan mereka dari kemungkinan orang-orang yang ingin terlibat secara aktif dalam konsolidasi nasional.
Hal ini tercermin dari jajak pendapat publik yang mengkonfirmasi menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi di daerah, menyisakan ruang untuk alternatif otokratis atau diktator. Preseden-preseden seperti ini memusatkan perhatian pada pembelaan dan hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan kebebasan berbicara dan pers.
Hak-hak ini akan selalu terancam, dan kita semua harus melindungi dan membentenginya secara permanen. Tidak membela kebebasan pers akan meningkatkan risiko pelemahan demokrasi, bahaya rezim tirani, dan lebih banyak ketidaksetaraan dalam masyarakat kita.***
Penulis Anggota Jaringan Islam Berkemajuan-JIB, Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada-KAGAMA Jakarta
Sumber: Media Indonesia.com